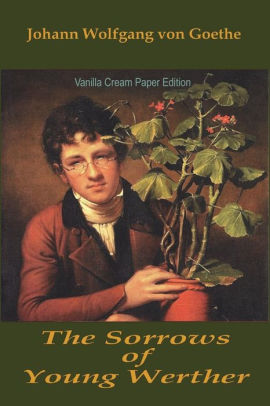Guru Sekolah Dasar saya yang boleh dibilang teladan bernama Sinta. Dia-lah yang senantiasa mendampingi saya mengikuti sejumlah lomba di mana saya menjadi juaranya dari tingkat kecamatan hingga kabupaten di tahun 1991. Ketika itu Banten masih dalam administrasi Provinsi Jawa Barat atau belum menjadi provinsi tersendiri.
Dia-lah yang mentraktir saya makan dan menyiapkan kebutuhan lomba saya dari kantong pribadinya. Sebagai wali kelas, barangkali ia merasa bertanggungjawab ketika ada siswa-nya yang bersaing dalam perlombaan yang sangat bergengsi.
Ketika itu saya dibonceng menggunakan motor Honda model lama-nya saat dari sekolah menuju lokasi perlombaan di sebuah sekolah yang dekat kantor kecamatan dan ke tempat perlombaan di kabupaten Serang (ketika itu masih masuk Provinsi Jawa Barat).
Ia juga guru sekolah dasar saya yang paling cantik. Rambutnya menyentuh dua pundaknya dan tubuhnya tidak pendek tapi juga tak terlampau tinggi. Hidungnya mancung. Ia tipe perempuan Sunda yang senyumnya akan membuat lelaki terpesona.
Mentalitas untuk bersaing dan berlomba secara sehat yang ditanamkannya untuk hal-hal yang positif dan meningkatkan prestasi serta kreativitas pada saya ternyata masih ada hingga saat ini, sehingga saya pun selalu tertarik ketika ada lomba menulis, contohnya.
Guru sekolah dasar saya yang bernama Sinta itu bisa menjadi teman bagi siswanya. “Biarpun kamu anak petani dan anak desa, bukan berarti kamu tidak pintar. Kamu harus buktikan bahwa kamu sama hebatnya dengan anak-anak kota yang banyak orang tua mereka adalah para pejabat itu….” Demikian diantara yang diucapkannya seingat saya.
Dan tentu saja ia sangat gembira ketika saya menjadi juara pertama pada perlombaan antar siswa atau pelajar itu, hingga kepala saya dikecup dan diciumnya. Barangkali karena saya telah membuktikan apa yang dinyatakannya kepada saya bahwa anak petani dan orang desa bukanlah anak yang tak berbakat dan memiliki potensi kecerdasan. Piagam perlombaan itu masih saya simpan saat ini, yang sekarang saya pahami sebagai dokumen kebudayaan pribada saya sendiri.
Guru saya itu pernah juga berkata kepada ibu saya bahwa saya anak yang terbilang bengal atau nakal, tapi cepat menguasai pelajaran yang diberikan guru-guru saya, sehingga selalu mendapatkan peringkat pertama ketika dibagikan buku raport siswa.
Saya akui saya memang seperti yang dikatakannya. Misalnya saya meletakkan tangkai pohon songler yang ada sejumlah ulat bulu berwarna hitam di meja siswa, sehingga dua siswi itu menyebut nama saya ketika ditanya oleh guru siapa yang melakukannya. Mungkin itu perbuatan iseng dan nyeleneh.
Dalam ingatan saya, di masa-masa sekolah dasar itu kami justru lebih banyak menghabiskan waktu kami dengan bermain dan saya hanya punya waktu membaca buku kesukaan saya di saat diminta ibu saya untuk menunggui padi-padi dari serbuan para burung yang akan memakan biji-bijinya yang mulai menui dan menguning sebelum dipanen. Kami bermain sampan dari pohon pisang, sepak bola, menerbangkan layang-layang dan yang lainnya.
Sesekali guru-guru kami memberikan tugas tambahan untuk dikerjakan di rumah, seperti menggambar, tapi tidak terlalu sering atau tidak terlalu rutin. Tentu saja yang saya gambar pada buku gambar saya adalah matahari, sawah-sawah, dan gunung yang terlihat samar tapi nyata dari rumah saya.
Ternyata, guru yang seperti Bu Sinta yang mengerti bakat siswa itu adalah contoh pengecualian dari kebanyakan para guru, karena guru yang semodel dia tak saya dapatkan ketika saya sekolah di sekolah menengah pertama saya dan sekolah menengah atas saya. Mereka memberikan materi dan lalu memberi instruksi.
Sekolah atau lembaga pendidikan kemudian menjadi institusi penyamaan yang bekerja tak ubahnya mesin, mencetak produk yang sama rata. Contohnya mencetak lulusan yang hanya menjadi buruh bagi kebutuhan industri kapitalisme atau birokrat. Ternyata, mekanisasi dan mesinisasi juga bermula dari dunia atau dari lembaga pendidikan yang hanya menjadi institusi indoktrinasi.
Yang demikian itu, contohnya, dilakukan orde baru Soeharto yang selama puluhan tahun melakukan propaganda dan indoktrinasi melalui mata pelajaran pendidikan moral pancasila dan pendidikan sejarah perjuangan bangsa, di mana materinya berujung atau mengerucut pada upaya untuk mengkultuskan rezimnya dan membungkam sikap kritis warga Negara.
Jika saja tak ada mata pelajaran seni, niscaya sebagian besar materi-materi yang diajarkan di sekolah kami itu tak lebih propaganda rezim orde baru yang meski korup tetap dibiayai IMF dan World Bank asalkan rezimnya patuh pada garis komando politik adidaya Amerika.
Ibu Sinta dan juga kepala sekolah saya ketika itu tidak ‘menghakimi’ saya hanya karena saya nakal dan Bengal, tapi justru ikut membidani termanifestasikannnya ‘bakat’ saya, sehingga mereka tidak memaksa agar saya menguasai dan menjadi apa yang bukan saya. Tapi coba anda lihat ribuan, mungkin jutaan skripsi para mahasiswa, tidakkah itu hanya kutipan dan copy paste belaka yang isinya hanya menurut si anu atau si itu.
Di sana tidak ada pikiran atau pendapat si mahasiswa itu sendiri kecuali deretan kutipan dan copy paste, padahal seorang penulis yang bernas kutipan hanya akan dianggap perlu dan menjadi penting dalam rangka membantu argument dan analisisnya sendiri tentang suatu peroslan atau ketika hendak menyatakan suatu tesis baru atau pandangan yang berbeda.
Sehingga ketika kita membaca skripsi, misalnya, yang panjang adalah kutipan dan copy paste-nya, bukan pendapat atau pandangan orisinil si penulisnya. Benar bahwa mengutip pendapat dan pandangan penulis lain itu perlu, tapi bukan berarti seperti menempelkan wajah orang lain ke wajah kita sendiri.